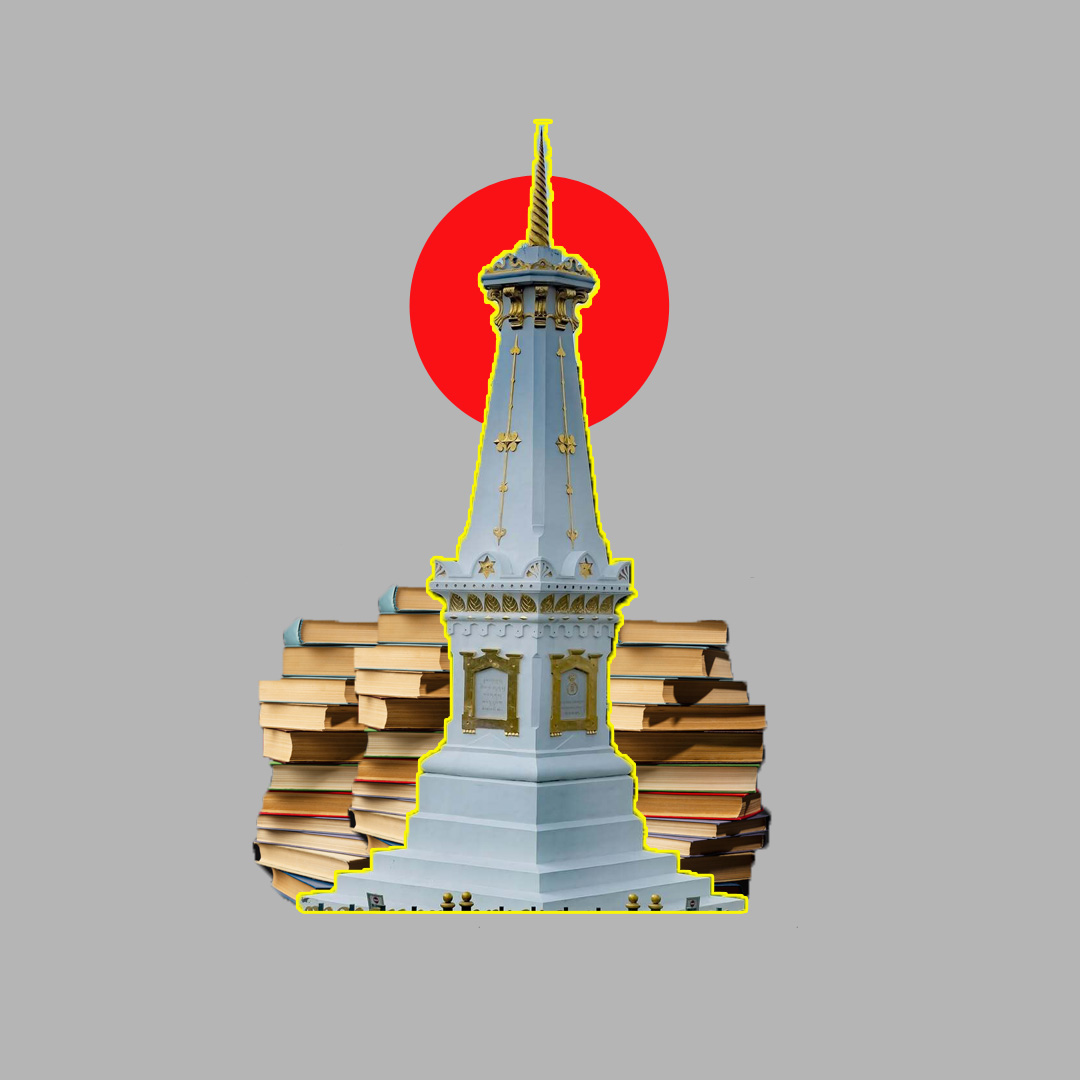Suatu saat bersama teman yang harus saya samarkan dengan Hamba Allah—kami melakukan perjalanan dari Kota Solo menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta. Hamba Allah adalah seorang pembaca tekun, maka tak mengherankan di sela waktu dalam perjalanan itu ia menyempatkan membaca buku. Meski tak bertahan lama, sebab ada kalanya ia membangun obrolan dan menanggapi percakapan yang saya lontarkan. Aktivitas saling bertindih, membentuk semacam pola.
Ada pengalaman yang membuat kami harus menceritakan dalam tulisan (NB: Hamba Allah di kesempatan lain akan bercerita tentang hal ini). Tiada lain dan tiada bukan adalah rupa-rupanya respons tak sedikit masyarakat kita di ruang publik, menganggap membaca buku semacam di atas transportasi umum adalah hal yang tidak lumrah. Bahkan, karena itu mungkin dianggap jarang terjadi, di beberapa kalangan muncul cara pandang yang terlampau berlebihan.
Seperti halnya adalah menganggap bahwa membaca buku di ruang publik itu adalah sesuatu yang luar biasa dan keren. Anggapan itu kok bagi saya membesitkan ada sesuatu yang keliru. Padahal, harusnya kita anggap lumrah dan biasa saja. Namun, masih menarik untuk menelaah akan mengapa anggapan tadi dapat muncul dan berlangsung. Jangan-jangan dikarenakan membaca buku di ruang publik itu adalah belum, atau tidak menjadi kebiasaan secara komunal, maka sekali muncul aktivitas itu akan menjadi pusat perhatian dan sanjungan.
Maka, ini akan menemukan kesamaan orang berbuat baik seperti menemukan barang tertinggal dan kemudian mengumumkan di media sosial. Mengapa yang terjadi justru banyak orang memberikan reaksi berupa apresiasi? Bukankah yang mesti dilakukan adalah menormalisasinya? Atau jangan-jangan fenomena ini membabarkan pada sesuatu hal, perbuatan baik itu tak lazim dilakukan. Itu nampaknya anggapan saya semata.
Namun masih menarik untuk mencurigai akan aktivitas membaca buku di ruang publik. Saya teringat pada sebuah esai garapan Idi Subandy Ibrahim berjudul “Buku dan Budaya Membaca” (Harian Kompas, 14 Mei 2022). Analisisnya menarik, bagaimana ia menyigi berbagai persoalan yang membuat gamblang akan tersendatnya akan kebudayaan membaca. Ia memberi penekanan, “Buku masih dianggap sebagai barang eksklusif.”
Baginya, kita telah masuk pada snobisme virtual. Kita makin jarang mendapati keteladan banyak pihak dalam politik membaca. Hal tragis diungkapkan oleh Idi dalam bagian penutup tulisannya. Jelasnya begini: “Mungkin itulah sebabnya beberapa pesohor, politisi, penceramah agama, bahkan ilmuwan lebih memilih menjadi youtuber atau influencer, karena generasi pasca-buku sedang tumbuh dan merayakan kemasyhuran virtual.”
Lantas, generasi macam apa yang dapat disematkan pada orang macam teman saya—Hamba Allah itu? Toh, bukankah bila dikonotatifkan, tindakannya hanya buang-buang waktu saja. Namun, saya kemudian berpikir pada konteks keberadaannya sebaga bagian urban yang kemudian berpengaruh pada prawacana atas tindakan yang ia pilih dan ia lakukan. Betapa pun hal itu kemudian berkait kelindan pada dimensi ruang dan waktu.
Mereka, para kalangan urban acap tertatih dan tergesa dalam menjalani rutinitas keseharian. Seperti dulu pernah diungkapkan Seno Gumira Ajidarma dalam esai “Menjadi Tua di Jakarta” (Majalah Djakarta! Edisi Maret 2005). Di tulisan itu terdapat kutipan bernada satire yang hingga kini terus diingat banyak orang. Seno menulis: “Bagi saya alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiunan tidak seberapa.”
Kutipan itu, seingat saya termasuk kutipan yang disukai oleh Hamba Allah. Saking sukanya, ia membeli kaus berdesain tulisan itu sejumlah tiga buah. Ia kerap memakainya saat akhir pekan, nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Pernah suatu waktu ia bercerita, bahwa saat bercengkerama dengan teman-temannya sembari mengenakan kaus itu: ia mendapati sebuah kemenangan atas kesibukannya menjalani rutinitas bekerja di kantor yang monoton. Walaupun, kecemasannya mudah muncul kembali saat Senin pagi.
Kemenangan yang ia maksudkan tentu saja adalah “kemenangan-kemenangan kecil”, saat dengan rendah hati di kehidupan urban ia merasa dan mengakui kalah dalam berbagai hal. Tak kecuali adalah direnggutnya waktu yang terkadang tak menyisakan sedikit pun untuk menemukan situasi yang dapat tergambarkan “menikmati waktu”. Termasuk adalah menggunakan waktu itu untuk membaca buku-buku yang telah lama ia beli. Ia merasa berdosa saat membiarkan buku-buku yang telah terbeli itu tergeletak tak keruan.
Apa yang dilakukan Hamba Allah kiranya adalah sesuatu tindakan sublim perlawanan terhadap ketegangan dan kekacauan dalam dunia urban. Mengupayakan untuk menggunakan waktu—bahkan terkesan “mencuri-curi waktu” meski hanya sebatas untuk buku. Keteguhan Hamba Allah itu pula kiranya menyembulkan semacam kritik untuk banyak kalangan, seperti pejabat dan politisi—yang terlihat punya banyak waktu luang, namun jarang memberi keteladanan dalam membaca.
Hamba Allah dalam membaca buku memang sadar bahwa menempatkan buku didasarkan pada keberadaan waktu luang. Ia tidak berangkat pada kesadaran atas kesadaran meluangkan waktu. Tindakannya mencuri waktu agar ia bisa membaca buku, sekalipun dalam ruang publik hendaknya dinormalisasi. Tidak perlu dinarasikan sebagaimana analogi di atas. Justru, rupanya satu hal yang meski kita bantu adalah pencarian lama Hamba Allah untuk menemukan toko buku yang sekaligus menjual waktu untuk membaca.
*Fisikawan Partikelir dan Penulis Buku Alam Semesta dan Kebudayaan Berpengetahuan (2025).