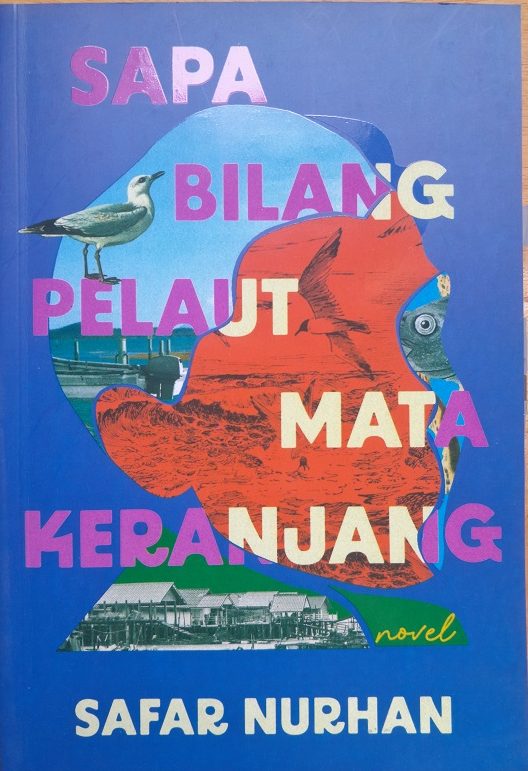Dan Tanda Tanya Lainnya
Banyak benda tidak saya dapati sebagai kunci penanda latar waktu, seperti televisi atau telepon genggam. Maka dari itu, imajinasi saya mengasumsikan cerita ini terjadi di masa silam. Ada satu penanda masa, yakni di Bab 11: tahun 90-an awal. Jika itu tidak keliru, berarti rentang waktunya tidak terlalu jauh.
Karena perbedaan budaya yang membentang antara Jawa dan Sulawesi, latar novel ini, tentu pembacaan saya hanya seadanya. Mereka, para tokoh, tentu memiliki karakter yang dipahami pengarangnya, sesuai dengan alamnya, yang jika dibaca-tafsirkan pembaca lain daerah, boleh jadi akan sangat berlainan. Maka dari itu, upaya pembacaan ini lebih banyak menghasilkan tanda tanya dan dugaan daripada pemahaman—tidak baik juga secara mudah menyimpulkan bacaan.
Itu semua sebab cerita ini cukup kompleks. Pembaca yang menduga pengarang akan membawa isu kesetaraan gender, terpatahkan oleh cerita yang tiba-tiba bergerak ke peristiwa perampokan; memberi gambaran kehidupan kelompok manusia dengan berbagai kepentingan. Kita mengira akan mendapat cerita ala detektif yang berusaha memecahkan misteri, menangkap perampok, atau hal-hal mengejutkan lainnya.
Ternyata tidak juga. Kita justru mendapat gambaran miniatur negara di Desa Masoni. Pihak yang semestinya bertugas melindungi dan menciptakan rasa aman tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik; sering mangkir. Warga, mungkin sudah terbiasa, tidak protes dan malah maklum dengan berkata, “Oh begitu,” terus menerus. Pemimpin, Kepala Desa, menjalankan tugas secara apa adanya, sebagai bentuk formalitas, tanpa gebrakanapa-apa—hanya untuk ngadem-ngademke.
Gambaran warga desa lebih mempeributkan absennya satu orang dalam agenda keamanan, alih-alih fokus pada persoalan perlengkapan melaut, tampak menarik. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, baik di dunia nyata maupun maya. Kita mudah hanyut dalam isu-isu kurang penting dan mengabaikan yang genting. Tidak heran jika kita mudah terprovokasi dan teranggap bodoh. Pembaca dapat seraya beristigfar ketika sampai di bagian cerita ini.
Peristiwa besar, perampokan itu, terjadi saat Ramadan, ketika Dewi dan Marlin kesiangan dan melewatkan sahur. Kita mendapat gambaran, masyarakat dalam cerita beragama Islam.
Uniknya, masyarakat ini tidak kebagian peran besar ahli agama. Biasanya, tokoh agama cukup memainkan peranan penting dalam menangani urusan di kampung, selain sebagai imam salat berjamaah. Minimal mereka mendapat saran untuk bersabar dan bertawakal ketika ada peristiwa besar. Agaknya, masyarakat itu sudah cukup rasional—atau justru jauh dari agama? Pembaca lagi-lagi mesti mengucap istigfar sebab kelewat takjub dan berburuk sangka.
Bacaan ini memang lebih banyak berisi cerita soal nelayan. Lebih tepatnya, kehidupan seorang nelayan muda yang tidak pernah benar-benar serius menjalani hidupnya-–melaut—sebab tidak punya perahu dan jarang menggerakkan tubuh mencari ikan. Ia tidak seorang diri. Teman sebayanya pun banyak demikian—banyak bercanda, bercerita, pesta, atau main halma di dego-dego.
Sejenak kita teringat Dataran Tortilla-nya John Steinbeck. Pemuda-pemuda dalam cerita tidak ada bedanya. Mereka hidup secara sembarangan dan seenaknya. Marlin tidak berubah hanya dengan pernikahan, meski itu hal besar sebab tidak semua orang berani dan punya cinta cukup besar. Mungkin, sebagaimana Steinbeck berkisah, butuh tragedi—peristiwa yang lebih besar dari perampokan dan penemuan benda aneh—untuk membuat mereka bertaubat dan menjalani hidup dengan baik, benar, bijaksana, penuh tanggung jawab, dan bersahaja. Atau, mungkin, mereka tidak perlu berubah sebab betapapun ugal-ugalan cara hidupnya, toh mereka tetap manusia. Dan itu cukup. Mungkin?