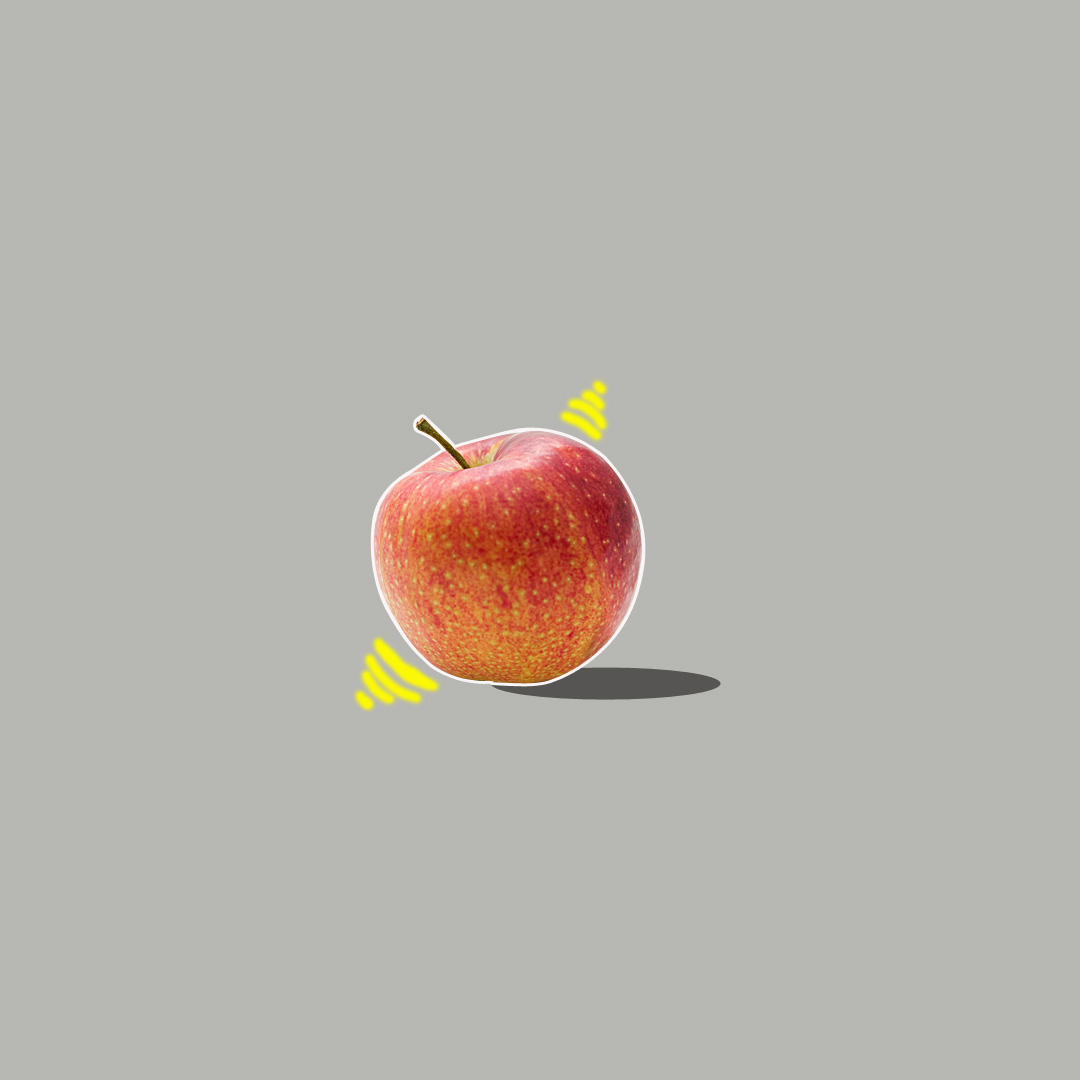Semisal datang pertanyaan, “Mengapa kaum miskin tak menyadari sebaiknya berhenti melarat?” dari Pablo Neruda, siapakah yang paling berhak menjawabnya?
Hari ini, orang terbiasa menjawab pertanyaan, bahkan cenderung gemar menandaskan pertanyaan-pertanyaan yang bertebaran di jagat maya. Ditanya apa rencana akhir pekan; apa yang sedang dipikirkan; apa yang terjadi; semuanya mudah terjawab.
Konon, karena hasil pendidikan yang buruk pula, orang lebih gemar menjawab, alih-alih bertanya. Menjawab pun itu sudah bagus daripada diam tak bersuara sama sekali.
Tak kurang, itu juga didukung minusnya kemampuan komunikasi publik para penguasa. Rakyat bertanya, lalu tanda tanya itu setia bertengger di mikrofon-mikrofon kepunyaan media massa dan tagar-tagar media sosial yang gemanya sumbang tapi tak cukup mengusik mereka.
Pertanyaan kemudian beranak-pinak dan dengan lekas menjadi yatim piatu. Tak ada yang mengasuhnya, tak ada yang membesarkannya, tapi mereka tumbuh dengan liar sekaligus baik.
Jika dihimpun, kita mungkin akan mencetak Kitab Pertanyaan, mengalahkan karangan Pablo Neruda, penyair kebanggaan Chili. Kumpulan pertanyaan kita akan lebih nyata dari sekadar pertanyaan Pablo yang—kita bisa menyebutnya—absurd. Sebaliknya, jawaban yang didapatlah yang sungguh di luar logika.
Tapi di hadapan pertanyaan di kalimat pembuka tulisan ini, rasanya tak seorang pun akan berani menjawabnya di situasi sekarang. Terlebih di Indonesia, pertanyaan Pablo memang sebaiknya anteng di halaman 53.
Sekian Dosa
Mengenal Pablo Neruda tanpa membaca puisi-puisi dan pidato nobelnya, kita hanya akan melihat dia sebagai orang berengsek. Kita mungkin akan dengan mudah menghakimi tindakannya yang, misal, menikah hanya karena kesepian, menelantarkan anak-istri, hingga dua kali berselingkuh.
Kemudian, orang akan menempelkan sifat-sifat kepujanggaan menjadi lekat pada dirinya. Mungkin sebagian memaklumi, sebagian lain tetap mengutuk. Tapi soal dosa tentu bukan urusan manusia.
Tanpa dikenai sanksi sosial ataupun cancel culture, Pablo tetap menjadi konsul, senator, hingga digadang-gadang sebagai calon presiden. Namanya tetap harum sebelum menjelang ajal. Rakyat lebih butuh negarawan yang cinta pada manusia, pada rakyat kecil, pada mereka yang tersingkir dari kehidupan, daripada sekadar tokoh yang harus tanpa cela.
Di pidato nobelnya (1971), kita membaca terjemahan: “Kami mewarisi kehidupan rakyat yang merana ini, yang menyeret-nyeret beban kutukan selama berabad-abad, rakyat yang paling memesona, paling murni, yang dengan bebatuan dan logam mereka ciptakan menara yang menakjubkan dan berlian yang memukau kilaunya—rakyat yang mendadak-sontak dirampok dan dibungkam di zaman gelap kolonialisme yang masih membekas hingga kini.”
Tentu ada orang-orang yang tidak percaya pada penyair hanya karena mereka menganggapnya cuma bisa berkata-kata, tak bisa mengurus negara. Tapi, toh, Pablo sendiri pada akhirnya memilih mundur dari pencalonan presiden dan memberi jalan sahabatnya, Salvador Allende, maju hingga menang.
Relasi Adalah Koentji
Pablo Neruda hanya seorang penyair yang juga kebetulan ingin menjadi orang biasa. Kata dia: “Seorang penyair harus ambil bagian dalam keringat, dalam roti, dalam anggur, dan dalam seluruh impian manusia. Cuma dalam jalan mutlak menjadi manusia biasa inilah kita memberi puisi keluasan tak terperi, yang sedikit demi sedikit mengelupas di setiap zaman.”
Ini pulalah yang dijalani tokoh Pablo Neruda si Penyair dalam novel karangan Antonio Skarmeta, Il Postino yang diterjemahkan Noorcholis: hidup dalam seluruh impian manusia. Tokoh Pablo telah memantik mimpi seorang tukang pos melalui metafora.
Mario si Tukang Pos itu pun akhirnya dapat memikat perempuan bernama Beatriz dengan sedikit metafora dan beberapa penggalan puisi si Penyair. Kedekatan Mario dengan Pablo yang suatu hari tampak di sudut kedai pun seolah menyampaikan bahwa orang sepenting Pablo sudi melancarkan urusan asmara tukang pos itu.
Mario belajar metafora langsung dari maestro. Dia bahkan sanggup membuat Pablo mau berbincang dengan calon ibu mertuanya, berusaha meyakinkan, mengatasi nasib cintanya yang menuju jurang kemalangan.
Pablo orang biasa, kendati perayaan hadiah nobel yang diterimanya diselenggarakan meriah di Isla Negra. Dia juga masihlah orang biasa sewaktu lulus studi dan dibukakan jalan karier oleh teman sekampusnya sebagai konsul kehormatan Chili. Teman sekampusnya itu memperkenalkannya pada Menteri Luar Negeri Chili saat itu, Conrado Rios Gallardo, sebagaimana yang ditulis Iswara N. Raditya dalam Jejak Kelana Pablo Neruda (2025).
Menjadi manusia biasa, artinya memelihara relasi baik dengan manusia biasa lainnya. Setelahnya, biar “keberuntungan” sendiri yang mengetuk pintu menuju jalan dan jalinan-jalinan keberuntungan lain.
Puisi Adalah ….
Setelah “mentas” dari kemelaratan akibat hanya berpuisi tapi lupa mengisi kantong, Pablo Neruda juga dikisahkan “menjerumuskan” orang lain ke dalam kubangan metafora. Kepada Mario, pengaruhnya amat besar. Selain sebagai comblang, dia juga seorang guru menulis hingga Mario mengirim puisi ke majalah kebudayaan La Quinta Rueda.
Menulis puisi sejak dini dan pada usia 13 tahun puisinya sudah dimuat di majalah La Manana, tentu menjadikan penghayatan Pablo akan puisi tidak dangkal. Dia hidup bersama puisi, dia menghidupkan puisi pada jiwa-jiwa yang berkobar seperti Mario.
Maka, kita tidak boleh ingkar ketika dia mendefinisikan “… puisi adalah sebuah tindakan, sekelebat atau khidmat, di mana kesunyian dan solidaritas, aksi dan emosi, kedekatan pada diri sendiri, pada umat manusia, dan pada manifestasi tersembunyi alam masuk ke dalamnya sebagai rekan yang sederajat.”
Dia telah menjalani sekian banyak kehidupan, baik yang terjal maupun yang tak diketahui khalayak, dan yang coba ia katakan adalah sesederhana bahwa puisi “tumbuh” bersama orang lain. Dengan jelas dia mengingatkan kita bahwa: “Tidak ada kesunyian yang tak teratasi. Semua setapak mengarah pada tujuan yang sama: menyampaikan pada orang lain siapa kita sejatinya. Dan kita mesti melewati kesunyian dan kesulitan, kesendirian, dan keheningan untuk mencapai tempat menyenangkan di mana kita bisa menarikan tarian aneh dan mendendangkan nyanyian pdih kita—namun dalam tarian atau nyanyian ini terlunaskan ritus paling tua dari suara hati kita, dalam kesadaran kita sebagai manusia dan dalam kesadaran kita untuk meyakini suatu suratan bersama.”
Pada akhirnya, kata kuncinya adalah “bersama”. Ini bukan semata persatuan klise dalam bingkai nasionalisme, pun perserikatan biasa. Lebih dari itu, sekaligus secara sederhana, “bersama” berarti sebagaimana semestinya yang manusia butuhkan dari satu sama lainnya.