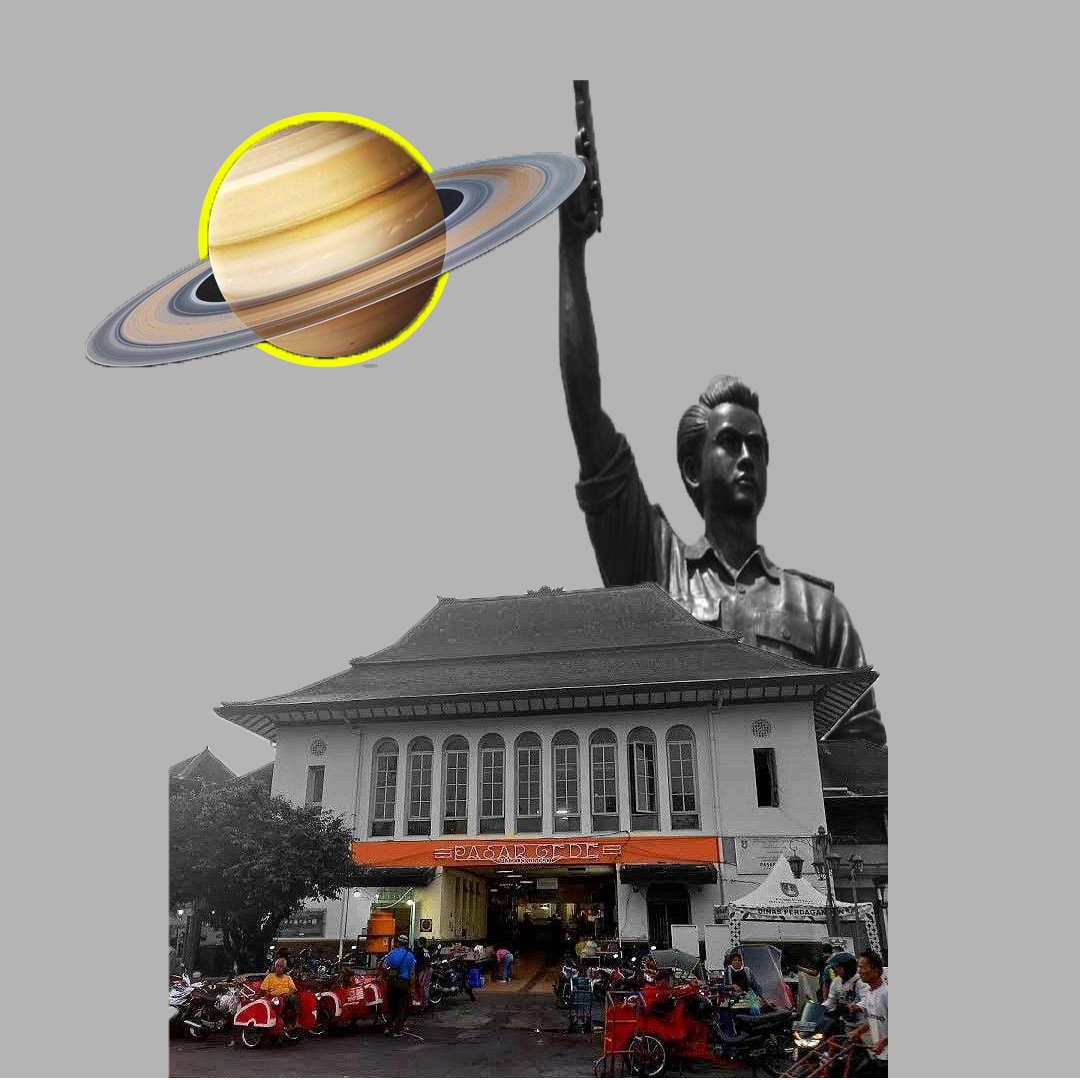Salah satu teman saya di instagram suatu waktu pernah mengutarakan pendapatnya. Kurang lebihnya begini: “Ning Solo, wonge soft spoken kabeh, ya, mas.” Kira-kira artinya begini, “Di Kota Solo, orang-orangnya berbicara dengan lembut semua ya, mas.”
Pernyataan yang diungkapkan oleh teman saya itu tak lepas dari kebelumpernahan dia menapakkan alas kaki di Solo. Ia baru sebatas punya cita-cita berkunjung ke Solo. Entah, kapan akan bisa direalisasikan. Yang pasti, pernyataan tadi menunjukkan bahwa keberadaannya tidak atau belum punya basis empiris.
Di manapun berada, untuk menguji keberadaan umpatan, saya rasa perhatian pentingnya pada jalan. Jalan itu ketika pagi beroperasi, menyambut para manusia menuju ke tempat kerja, sekolah, hingga pasar. Di sana menyembulkan pertarungan, pertaruhan, dan pengharapan.
Betapa pun kita paham, sekalipun memiliki wilayah yang kecil, Solo menjadi ruang pergerakan kalangan urban. Mereka yang berasal dari luar daerah, menjalani misi untuk sekadar melanjutkan pendidikan, atau sampai menjalani rutinitas pekerjaan. Harus diakui, banyak jalan di Solo dalam waktu tertentu tak luput menderita kemacetan.
Dengan begitu, jalanan menjadi saksi akan munculnya situasi berdesakan, saling serobot, dan berebut kecepatan. Di sanalah gejolak itu terjadi, membuncah—meski tanpa pandang bulu, kita harus jujur, bahwa yang menang tetap kapitalisme dengan penguasaan berbagai lini.
Untuk mendasarkan pada asas empirisme, hampir saban pagi saya menyaksikan bagaimana pergerakan yang terjadi di pertigaan Tugu Makutha. Tugu di sana sebagai simbol masuk Kota Solo. Sementara arus sebaliknya, dari timur ke arah barat, meninggalkan Solo untuk menuju Colomadu (Karanganyar), Boyolali, Yogyakarta, hingga Semarang.
Di pertigaan itu ada jalan kecil yang membentang ke selatan, sebagai alternatif menuju Kartasura, seperti kampus Universitas Muhamamadiyah Surakarta, Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso, Universitas Pignatelli Triputra, hingga Pasa Kleco. Dengan sematan “alternatif”, saban hari, jalur yang merentang di kelurahan Karangasem itu selalu ramai.
Terbilang, jalan itu berada di wilayah perkampungan, meski lebih lebar dari biasanya. Yang perlu dipahami, di simpangan yang ada, tak tersedia instrumen macam lampu lalu lintas atau relawan macam Pak Ogah. Dengan tujuan membagi kesempatan dan waktu bagi semua pengguna dari arah mana pun dalam persimpangan. Modal mendasarnya bersandar pada toleransi dan kerendahan hati.
Namun, pada jalan di waktu pagi dengan penuh desakan, ketergesaan, dan keramaian, harus diakui tak sedikit pengguna jalan memiliki kecenderungan yang sama: tidak mau mengalah. Beberapa peristiwa pernah terjadi, seperti tak menengok kanan-kiri saat mau menyeberang dan menyalip dengan membahayakan pengguna dari arah berlawanan. Itu berdampak pada antarkendaraan yang berserempetan.
Ada fenomena yang mengemuka dalam kenyataan tersebut. Interaksi sosial yang tinggi memang memicu adanya ketegangan, sebagaimana gagasan filsuf dan sosiolog Jerman, Georg Simmel dalam esainya berjudul “The Metropolis and Mental Life” (1903). Jalan telah memberi beban makna yang terlampau konotatif bagi kota dan kalangan urban. Rupa-rupanya, terendus bahwa harus diakui ketidaksabaran dalam mengurai kemacetan dan melintasi jalanan—telah membawa kita menjadi makhluk yang memendam amarah.
Perasaan itu memang kadang tidak langsung diungkapkan. Sebatas dibatin dan hanya disimpan dalam perasaan. Perasaan itu merupakan akumulasi keterhubungan jalan, kepentingan, dan pengguna lainnya. Setiap pengguna kendaraan, bisa memendam amarah dalam susunan umpatan. Ini tentu menjadi mekanisme pertahanan diri, sedang pada hal lain merasakan banyak kekalahan.
Ketegangan yang terjadi di jalanan, rupa-rupanya telah membawa pada perubahan makna dalam hiruk-pikuk perkembangan kota. Perubahan itu tragisnya juga mampu menggeser pada aspek kebudayaan. Pendapat kawan saya tadi nampaknya masih bisa dikoreksi: di Solo, mengumpat itu memang diperbolehkan. Anda ingin mengumpat?