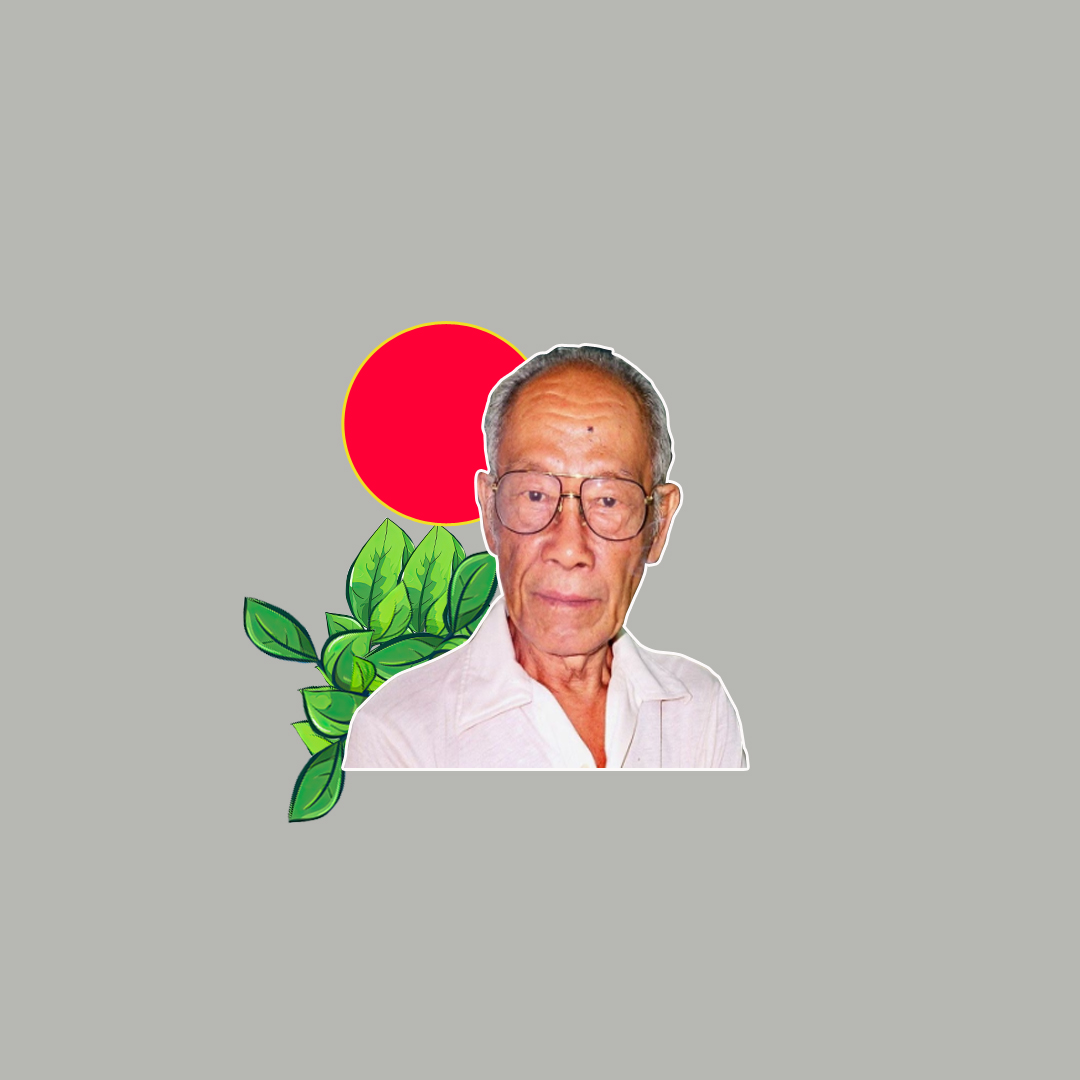Hampir setengah abad lalu sebuah surat Pram tulis dan baru dapat kita baca sekitar seperempat abad ini. Kita membacanya dalam bentuk buku setebal 240-an halaman. Darinya kita mendapatkan informasi, rahasia, sekaligus pesan.
Demikianlah Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer yang baru terbit pertama kali pada 2001 silam. Pram menulisnya dalam bentuk surat. Terasa lebih personal sekaligus senyata-nyata memberi “warisan ingatan” kepada pembaca.
Lain dengan tetralogi Buru yang dikemas dalam bentuk prosa, buku ini berisi catatan sekaligus memuat data dan ingatan. Mungkin Pram sengaja membentuknya dalam format surat, alih-alih fiksi, sebab dia sudah berhitung agar buku ini dapat menjadi rujukan, bukan karya yang kemudian dapat secara bebas ditafsirkan sesuai konteks zaman.
Redaksi mengatakan, tulisan Pram tidak sempurna dan baru kemudian mengalami penambahan atau penyesuaian, disertai keterangan yang dapat memangkas jarak generasi pembaca dan penulis. Tentu kita maklum sebab Pram sendiri menulisnya dalam keadaan menjadi tahanan. Dia bukan orang bebas dan merdeka untuk menulis.
Kita yang membacanya pun, jika cermat, akan menemui kekacauan-kekacauan. Bahkan, tulisan berformat surat ini memuat informasi inti hanya sekitar 45 halaman. Sisanya, 200 halaman berisi catatan pengalaman.
Pram berkisah, berbagi pengalaman, berbagi catatan perjalanan, selama mencari jejak keberadaan orang-orang buangan di Buru, mereka yang semula para perawan remaja yang menjadi budak seks para kolonial Jepang. Pembaca bisa saja mengira, Pram seorang antropolog atau etnografer. Dia bercerita dengan baik, detail, dan amat memahami kondisi geografis.
Sebagai orang asing, tahanan dari Jawa di Buru, dia mahir menyebut nama-nama tempat. Dia pun tidak buta arah mata angin. Lebih dari itu, dia bahkan tahu kondisi wilayah, bentang alam di sekitarnya.
Pembaca yang cermat akan dapat membayangkan letak-letak geografis yang disebutkan Pram. Sementara itu, pembaca yang baik akan mengambil selembar kertas untuk membuat coretan-coretan sesuai yang dibacanya. Singkatnya, tulisan Pram bukan tulisan sepintas lalu. Kita butuh memindahkan gambaran yang ada di kepala Pram yang dia tuangkan dalam tulisan itu ke dalam gambar baru, memvisualisasikannya di selembar kertas.
Selain memahami geografi atau ilmu kebumian, dia membagikan ingatannya, catatannya mengenai adat Buru. Dia bahkan mengerti bahasa Buru! Banyak hal telah Pram lalui sebagai tahanan. Dia berinteraksi dengan masyarakat adat Buru yang dia anggap, untuk ukuran zaman 70-an, masih terbelakang. Bukan tanpa alasan, tentunya, dia menyoroti hal-hal tersebut. Pasalnya, dia memiliki kepentingan untuk mencari perempuan-perempuan Jawa yang dibuang di Buru. Namun, ketentuan adat menghalanginya menemukan apa yang dia cari.
Pertama, perempuan dalam adat masyarakat Buru diserupakan seperti harta benda sehingga mereka dibatasi untuk bertemu hingga mengobrol dengan orang lain. Bahkan, mereka tidak boleh berbahasa selain menggunakan bahasa Buru.
Sayangnya, masyarakat Buru tampaknya, sesuai dengan deskripsi Pram, tidak mengenal budaya baca-tulis. Kendati memiliki bahasa sendiri, Pram tidak menyebut—atau mungkin saya luput—aksara bahasa itu sendiri. Maka, dia tidak mendapat keterangan, jawaban, baik dalam bentuk lisan karena batas-batas adat maupun tulisan.
Sebagai seorang tahanan yang kebebasannya dirampas, rasanya wajar jika Pram geram dengan adat yang konyol dan membelenggu. Dia berkali-kali memberi penjelasan pada pembaca soal situasi-situasi yang terjadi dalam dinamika masyarakat adat tersebut. Mulai dari perempuan tidak boleh berbicara dan berbahasa selain dengan bahasa Buru, anak dan pemuda yang tidak boleh berpendidikan sebagaimana “penduduk daratan”, ketidakpercayaan pada modernitas, hingga ternyata “raja” atau pemimpin daerah itu bisa baca-tulis dan berbahasa Indonesia—jika tidak salah ingat.
Ada kekuasaan yang membatasi kebebasan dan itu kita baca sebagai bentuk adat yang kolot. Kita pun dongkol, meski berkali-kali Pram juga menggambarkan bahwa dirinya dan teman-teman seperjalanannya itu menghormati dan menghargai adat. Namun, kita juga bisa saja bertanya, nada penceritaan Pram yang berkali-kali menyinggung kekakuan adat itu apakah sebab dia terlalu memuja modernitas atau semata sebentuk kemarahan karena telah direnggutnya kebebasan yang seharusnya dia miliki?
Tapi nanti dulu, lah. Lagi pula, kritiknya terhadap adat ini masuk akal pula. Terlebih, cara penceritaannya, sebab dia juga pengarang, telah berhasil memancing emosi pembaca. Betapa tidak, dalam bab akhir buku ini, bab terpanjang, setidaknya telah dua kali Pram menceritakan ketegangan antara kelompok tahanan dan masyarakat adat Buru.
Jika pembaca telah dibikin menangis karena mendapati kisah para perempuan yang ditipu, dipaksa menjadi budak seks, hingga dibuang tanpa bisa kembali ke kampung halaman sebab malu dan terhalang adat, pembaca pun bisa kembali menangis ketika Pram mengisahkan kehidupan orang Buru. Masyarakat adat yang hidupnya masih bergantung pada hutan itu digambarkannya hanya makan jika perlu, tidak setiap waktu secara teratur melakukan aktivitas paling penting untuk kebutuhan jasmani.
Pram dan kawan-kawannya nyaris berperang dengan warga sebab terjadi kesalahpahaman. Namun, yang mengharukan adalah beberapa orang Buru itu berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mematuhi perintah untuk menyerang dari pimpinan adat. Mereka melindungi tamu mereka dan menganggapnya sahabat setelah beberapa kali dibawakan garam, beras, kopi, gula-gula, hingga pakaian.
Kita melihat Pram dan rombongan seperti sekelompok mahasiswa yang sedang KKN. Salah satu akrab dengan bocah hingga memandikannya, satunya lagi mengobati dan berperan jadi tabib atau dokter, sementara seorang lagi berulah hingga berselisih dengan kepala adat.
Mereka membawa barang-barang sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah diterima. Mereka disambut, dirayakan, bahkan diajak “berpesta” sederhana. Bahkan, mereka memiliki program kerja, bertemu dengan perempuan buangan yang diceritakan masih hidup, meski tanpa keterangan jelas hingga nama pun hanya sepotong informasinya.
Mungkin juga mereka memiliki “misi” terselubung. Dengan kedatangan mereka, masyarakat adat berkenalan dengan “peradaban modern”, berkeinginan bisa baca-tulis, dan perlahan sadar bahwa mereka sedang dibelenggu oleh adat dan pamali.
Satu adegan kocak terbaca ketika mereka memberi waktu kepada salah seorang warga untuk membaca mantra-mantra di samping pasien terduga rabies usai digigit anjing. Padahal, penanganannya butuh lekas. Kita pun sedikit pekewuh untuk tertawa dan memilih meredam amarah.
Pram amat detail sebagai pengisah. Pembaca tidak hanya membutuhkan selembar kertas untuk menggambar bentang alam yang dideskripsikannya, tetapi juga meliputi silsilah keluarga beserta nama panggilannya. Kita amat mudah dibingungkan dengan hal itu jika tidak berhati-hati selama membaca.
Sikap itu menjadi penanda bahwa Pram betul-betul menjalani dan menikmati perjalanannya. Dengan baik dia gambarkan latar beserta suasana-suasananya, pun orang-orangnya. Dia bahkan sempat melucu beberapa kali. Digambarkannya keberadaan anak kecil dengan ingus panjang dan hijau. Sedetail itu! Lain halaman, kita melihat keakraban rombongan dengan guyonan recehnya. Padahal, situasi saat itu sedang tegang dengan nyawa sebagai taruhannya. Sempat-sempatnya dia melucu!
Kita kemudian paham, dengan status sebagai orang buangan, dia tidak memiliki apa-apa untuk dibagikan. Waktu pun terbatas. Kita bisa saja menyayangkan kenapa rombongannya tidak mengajarkan pemuda dan anak-anak Buru baca-tulis. Kita lalu mengandaikan, mereka memberi kertas dan buku pada masyarakat adat. Sudah macam mahasiswa KKN saja!
Tapi berbicara soal kertas, selain kita butuhkan untuk memindahkan imajinasi menjadi gambaran visual nyata, kita dapat menyayangkan hal yang lebih besar lainnya. Andai saja saat itu ada perintah tertulis di atas kertas soal pengiriman perempuan-perempuan pribumi untuk belajar ke Jepang. Atau, minimal ada pemberitaan di media cetak terkait hal ini yang nantinya bisa dijadikan sebagai arsip dan berguna untuk menuntut para penindas itu.
“… janji menyekolahkan ke Tokyo dan Shonanto oleh Pemerintah Pendudukan Balatentara Dai Nippon, yang tidak pernah diumumkan dengan resmi, terutama tidak pernah tercantum dalam Osamu Serei (Lembaran Negara), adalah suatu kesengajaan untuk menghilangkan jejak perbuatan agar orang tak mudah menjejak kejahatannya.” (halaman 15 cetakan ke-33).